Bab 3: Syekh dari Timur
Langit mendung ketika Syekh Syiah Hudam menapakkan kaki di pelabuhan tua Lhokseumawe. Jubahnya sederhana, sorbannya lusuh, namun matanya menyala oleh cahaya yang berasal dari dalam. Ia bukan ulama biasa. Ia telah mengembara dari Hadhramaut, menempuh ribuan mil perjalanan mencari petunjuk, dan kini ia merasa langkahnya dituntun oleh takdir.
Ia pertama kali mendengar kisah Putroe Neng di masjid kecil pesisir. Kisah wanita yang bersuamikan sembilan puluh sembilan pria, semuanya mati dengan cara yang sama. Rakyat mulai menjauhinya, sebagian mencibir, sebagian memujanya, namun semua menyimpan rasa takut. Bagi Syekh Hudam, itu bukan alasan untuk lari. Justru itu panggilan.
Ia tidak datang sebagai pelamar. Ia datang sebagai penuntun. Dengan izin istana, ia mendekati Putroe Neng bukan sebagai seorang lelaki yang ingin memiliki, tapi sebagai seorang yang ingin menyembuhkan. Mereka mulai berbincang di serambi istana, kemudian di taman, lalu di mushalla kecil tempat Putroe Neng biasa menyepi. Malam-malam panjang mereka isi dengan berdzikir, membaca kitab, dan saling diam dalam damai.
Waktu berjalan. Rakyat mulai memperhatikan perubahan dalam diri sang putri. Ia tampak lebih tenang, lebih lembut, namun tetap tegar. Senyumnya perlahan kembali, dan mata yang selalu menyimpan luka kini mengandung harapan.
Setahun berlalu. Syekh Hudam pun mengutarakan niatnya. "Aku tak ingin menjadi yang ke seratus, Putroe Neng. Aku hanya ingin menjadi yang terakhir," katanya lirih. Perempuan itu menunduk, matanya berkaca. "Jika kau mati seperti yang lain...?" tanyanya takut.
"Maka aku mati dalam ikhlas. Tapi jika hidupku bisa menyembuhkanmu, maka itu pun takdirku."
Mereka menikah di bawah langit yang cerah, dengan saksi laut dan angin. Rakyat yang dulu takut kini berkumpul dan mendoakan. Malam pertama itu, tidak ada aroma kematian. Hanya keheningan penuh harap dan cahaya rembulan yang menyinari ranjang mereka.
Keesokan paginya, untuk pertama kali dalam sembilan puluh sembilan malam pengantin, Putroe Neng tidak menangis. Dan dari kamar itu, Syekh Hudam keluar dalam keadaan hidup.
Namun perjalanan mereka belum selesai. Kutukan belum sepenuhnya musnah. Maka Syekh Hudam memulai ritual panjang: ia mengumpulkan ramuan dari akar gunung dan kerang laut, menghisap racun dari tubuh istrinya menggunakan bambu yang dibelah, dan membuang sisa racun itu ke dua tempat suci: Gunung Seulawah dan Selat Malaka.
Petir menyambar langit saat racun itu dibuang. Beberapa penduduk bersaksi bahwa malam itu langit Lhokseumawe berubah warna. Tapi sejak saat itu, tubuh Putroe Neng menjadi ringan. Ia tak lagi takut disentuh. Tak lagi takut mencintai.
Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang panjang, ia merasa bebas dari warisan darah yang membunuh.
(Bersambung ke Bab 4)
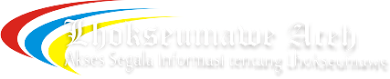








0 Comments