Bab 4: Damai yang Tak Bernama
Musim hujan datang ke Lhokseumawe dengan tenang. Hujan turun lembut di atas atap istana, membasahi halaman tempat bunga-bunga kenanga ditanam Putroe Neng dengan tangannya sendiri. Ia tak lagi mengenakan zirah perak, tak lagi memegang pedang. Kini ia memakai baju panjang berwarna tanah dan kerudung sederhana. Di matanya ada cahaya baru: cahaya perempuan yang telah melalui badai.
Syekh Hudam menjadi teman hidup yang tidak pernah mengurung. Ia mendampingi Putroe Neng seperti bayangan yang tak memaksa, memberi ruang bagi sang istri untuk menemukan dirinya sendiri. Bersama mereka membangun surau kecil di luar kota, tempat anak-anak belajar mengaji dan para perempuan diajarkan ilmu pengobatan.
Setiap minggu, Putroe Neng berjalan kaki ke desa-desa, membawa minyak atsiri, daun bidara, dan ramuan warisan neneknya—kini digunakan untuk menyembuhkan, bukan membunuh. Ia tidak lagi dihantui oleh masa lalu. Tapi bayang-bayang itu tak sepenuhnya pergi.
Kadang, di tengah malam, ia terbangun. Ia melihat mimpi-mimpi lelaki yang pernah menjadi suaminya. Wajah-wajah mereka muncul seperti kilasan kabut. Beberapa ia ingat namanya, beberapa tidak. Tapi semuanya ia kenang. Ia menyalakan pelita dan berdoa satu per satu, menyebut mereka dengan panggilan lembut: "Maafkan aku."
Rakyat mulai memanggilnya "Ummi Seratus"—bukan karena jumlah suaminya, tapi karena kasih sayangnya kini seperti seratus pelukan. Ia menjadi simbol pengampunan, keteguhan, dan keajaiban. Tak ada perempuan sekuat dia, tak ada kisah cinta seaneh miliknya.
Namun hidup tetap bergerak. Tahun-tahun berlalu. Syekh Hudam mulai menua, dan Putroe Neng pun demikian. Suatu malam, ketika hujan turun tanpa suara, sang syekh berpulang dalam tidur. Ia tersenyum, seolah telah menyelesaikan tugasnya.
Putroe Neng menguburkannya sendiri, di samping surau kecil mereka. Tak ada upacara megah, hanya doa dan bunga putih.
Setelah itu, Putroe Neng jarang terlihat. Ia tinggal di surau, duduk di serambi, memandangi laut yang dulu membawanya ke negeri ini. Beberapa mengatakan ia wafat dalam sunyi. Beberapa lagi percaya tubuhnya lenyap dibawa angin.
Namun makamnya tetap ada. Di Blang Pulo, tak jauh dari laut, ada sebuah nisan tanpa nama. Dan di sekitarnya, deretan batu kecil, sembilan puluh sembilan jumlahnya, berdiri diam seperti penjaga kisah lama.
Dan orang-orang masih datang. Berziarah. Berdoa. Bertanya: bagaimana mungkin seorang perempuan mencintai sembilan puluh sembilan kali, dan tetap bertahan untuk cinta yang keseratus?
Mungkin karena ia bukan hanya perempuan. Ia adalah legenda.
Tahun-tahun setelah kepergian Putroe Neng menjadi masa penuh cerita. Kisahnya hidup dari mulut ke mulut, berubah menjadi legenda yang menembus batas usia dan generasi. Di antara anak-anak yang mengaji di surau tua dekat laut, nama Putroe Neng disebut dengan hormat, dengan bisik haru, dengan rasa bangga.
Makam tanpa nama itu kini menjadi tempat ziarah. Orang datang dari berbagai penjuru Aceh, bahkan luar negeri, membawa bunga dan doa. Mereka tak lagi takut dengan kisah kutukan. Sebaliknya, mereka mencari berkah dari jejak perempuan yang mampu menanggung sembilan puluh sembilan luka, dan tetap memiliki hati untuk mencintai yang keseratus.
Beberapa sejarawan mencoba menulis ulang kisahnya dengan logika. Mereka menyebutnya fiksi. Mereka mempertanyakan kebenaran jumlah suami, menganggapnya metafora atas penderitaan. Namun rakyat tidak peduli. Karena dalam hati mereka, Putroe Neng bukan sekadar nama. Ia adalah kekuatan yang nyata, yang tak membutuhkan pembuktian.
Surau yang dulu ia dirikan tetap berdiri. Meski atapnya mulai lapuk, lantainya retak, namun suara anak-anak mengaji tak pernah berhenti. Perempuan-perempuan masih mengajarkan ramuan dari daun-daun yang ia tanam. Dan laut—laut yang dulu membawanya dari negeri jauh—tetap memeluk garis pantai Lhokseumawe, seolah menjaga rahasia yang tak akan pernah diungkap.
Di antara malam-malam tenang, kadang terdengar suara pelan dari arah pantai. Beberapa nelayan bersumpah mereka melihat sosok perempuan berkerudung tanah berjalan di antara batu-batu nisan. Ia tak berbicara, hanya menatap bulan, lalu menghilang di balik kabut.
Putroe Neng mungkin telah tiada.
Namun cinta, keberanian, dan pengorbanannya—hidup selamanya.
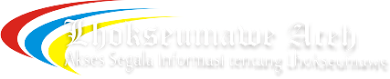








0 Comments